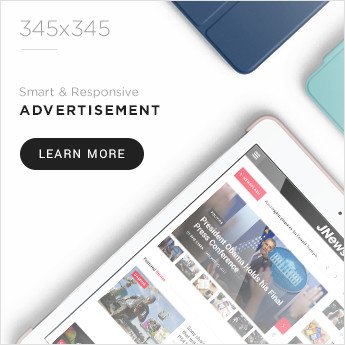Belum lama ini kita mendengar kabar dari Dewan Pers: ratusan jurnalis di-layoff, di-PHK. Banyak media gulung tikar. Sekian brand media yang kita kenal beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi. Masih adakah masa depan untuk jurnalisme?
Saya Wahyu Dhyatmika. Selamat datang di Kelas Pakar.
What’s wrong with journalism?
Apa sih yang salah dari jurnalisme?
Kita mendengar banyak sekali kabar buruk dari dunia industri media belakangan ini. Ratusan wartawan dan pekerja media di-PHK. Beberapa media memutuskan tutup, tidak lagi beroperasi. Nama-nama media yang sebelumnya akrab kini sering kali sulit diakses, tidak lagi beredar.
Di mana sebetulnya masalahnya?
Banyak riset menunjukkan setidaknya ada tiga isu besar yang dialami jurnalisme sejak disrupsi digital—yakni sejak terjadi perubahan platform dari konvensional (cetak, radio, televisi) menjadi digital. Tiga isu yang paling sering dikaitkan dengan kemunduran jurnalisme adalah:
- Kemunduran dalam menjangkau khalayak (reach) yang berkurang drastis.
Kita lihat pengguna media sosial di Indonesia bisa mencapai ratusan juta. Sementara itu, satu media online rata-rata hanya memiliki monthly active user antara 15 sampai beberapa juta. Itu pun sudah tergolong bagus—rata-rata bahkan lebih kecil dari itu. Artinya, banyak konten berita dan konten jurnalistik tidak menjangkau khalayak ramai. Ada problem reach. - Engagement yang minim.
Ketika terjadi masalah keterjangkauan, maka terjadi juga masalah keterlibatan. Tidak ada interaksi yang memadai antara jurnalisme dan audiensnya. Berita dibaca sambil lalu. Tidak ada diskusi, tidak ada percakapan yang tercipta dari informasi-informasi yang dipublikasikan media. - Kehilangan kepercayaan (trust).
Banyak orang tidak lagi percaya pada berita, tidak lagi percaya pada jurnalisme. Dengan ketiga isu ini, lengkap sudah problem jurnalisme saat ini.
Maka muncul pertanyaan: apakah jurnalisme masih punya masa depan? Masih adakah jurnalisme lima atau sepuluh tahun dari sekarang?
Jika kita bedah lebih dalam, akar persoalannya adalah krisis model bisnis. Media memilih model bisnis yang tidak sejalan dengan manfaat yang diberikan oleh produknya. Jika kita kembali ke teori business model, terdapat dua elemen penting: value creation dan value capture.
Sebuah produk harus bisa menciptakan nilai yang berguna bagi penggunanya. Dari manfaat inilah muncul monetisasi. Jika ini terjadi, maka tercipta siklus: produk dilempar ke pasar → manfaat dirasakan oleh audiens → audiens memberikan reward finansial kepada produsen. Namun, banyak media melakukan kekeliruan dalam memilih model bisnis.
Satu contoh, organisasi media memilih hidup dari iklan berbasis impression—yang muncul ketika pengguna tertarik secara sekilas terhadap konten. Judulnya menarik, atau isunya sensasional. Konten semacam ini menghasilkan klik, menghasilkan impression. Ketika itu terjadi, penghasilan pun masuk ke media.
Akibatnya, media berlomba-lomba membuat konten yang mengejar impression—bukan manfaat. Lahirlah clickbait. Kita kemudian terpesona (atau justru terenyuh) melihat berita-berita remeh-temeh yang sebetulnya tak layak diberitakan.
Banyak kode etik jurnalistik dilanggar demi mengejar klik. Memang ada pemasukan, tapi kepercayaan publik terkikis. Media menggali lubangnya sendiri: dapat reach, tapi minim engagement; dapat revenue, tapi kehilangan trust.
Dalam jangka panjang, media mengalami krisis model bisnis. Saat algoritma pendapatan iklan berubah, media tidak bisa keluar dari perangkapnya sendiri. Model bisnis lain yang umum dipakai media adalah iklan tradisional.
Namun, iklan ini tidak berbasis performa. Pengiklan membayar slot atau inventori di media bukan karena performa media, tetapi demi menjaga hubungan baik. Di sinilah muncul dua masalah:
- Ketika media tetap kritis pada pengiklan, maka pengiklan merasa tak mendapatkan value dan memutus kontrak.
- Di sisi media, karena hanya bergantung pada hubungan baik, mereka tidak membangun kemampuan deliver performance—tidak punya tim teknologi atau marketing yang kuat.
Media akhirnya tidak lengkap sebagai institusi digital. Ketika anggaran iklan dipotong, media kehilangan porsi besar pendapatan dan terpaksa mengurangi tenaga kerja.
Ke depan, kita butuh solusi permanen untuk masa depan jurnalisme.
Jika kita sepakat bahwa jurnalisme adalah public goods—instrumen penting bagi masyarakat demokratis dan pasar yang sehat yang membutuhkan informasi lengkap, akurat, dan kredibel—maka semua pihak harus bersama-sama memecahkan krisis model bisnis ini.
Pertama, media harus kembali ke audiensnya. Media harus memahami apa yang dibutuhkan pembacanya. Ada riset menarik dari BBC tentang user needs:
User mencari informasi untuk:
- To do: melakukan sesuatu.
- To understand: memahami sesuatu.
- To feel: merasakan emosi tertentu.
- To know: mendapatkan pengetahuan baru.
Dari empat area tersebut, ada delapan elemen kebutuhan pengguna yang bisa dipenuhi media. Apakah itu:
- Update me: beri saya pembaruan.
- Inform me: beri saya informasi.
- Entertain me, Distract me: hibur saya, alihkan perhatian saya.
- Inspire me: beri inspirasi.
Semua ini bisa menjadi panduan media dalam merumuskan kebijakan editorial yang audience-centric.
Di sisi ekosistem, kita semua juga bertanggung jawab memastikan jurnalisme sebagai public goods tidak mati. Saat ini sedang dibahas inisiatif seperti journalism trust fund—semacam dana abadi jurnalisme. Setiap pihak yang merasa mendapat manfaat dari jurnalisme bisa chip in, memberikan kontribusi.
Dana ini dapat digunakan untuk membiayai liputan-liputan penting, serta eksperimen model bisnis baru agar media bisa lebih berkelanjutan (sustainable).
Jika kita percaya bahwa jurnalisme itu penting, maka kita harus bersama-sama mencari solusi. Agar krisis jurnalisme ini bisa kita lewati, dan masyarakat tetap bisa menikmati sajian informasi yang terverifikasi dan sesuai dengan kepentingan publik.