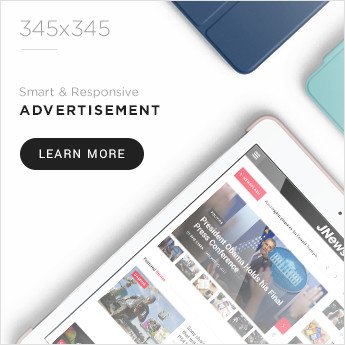Pada tahun 1993, sekitar bulan April lampau, saya berkunjung ke rumah Prof Dr. Ida Bagus Mantra, mantan Gubernur Bali yang termashur, mantan Duta Besar Indonesia untuk India, mantan Rektor Unud, penerjemah Bhagawadgita. Kunjungan itu dalam rangka memohon kesediaan beliau menjadi penasehat Panitia Kongres Nasional I Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang saya pimpin sebagai ketua umumnya. Kunjungan itu juga atas masukan dan saran Gubernur Bali ketika itu, Prof. dr. Ida Bagus Oka. Saya mengajak beberapa rekan ke rumah Bp Ida Bagus Mantra., diantaranya Nyoman Dawan, Made Nurbawa dan Komang Sumber Adiputra semuanya mahasiswa Unud, adik kelas dari fakultas berbeda.
Saat tiba di rumah beliau di Sumerta Kelod, kami tidak begitu yakin, Pak Mantra akan menerima kami, sekelompok anak muda yang hadir tanpa dampingan figur tetua dan belum pernah ke sana. Kami juga tidak memiliki banyak pengetahuan untuk bercerita dengan beliau karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Kondisi kesehatan beliau saat itu tidak baik. Beliau bed rest karena sakit.
Orang pertama yang mengetahui kedatangan kami adalah tukang kebun. Dia mengarahkan kami untuk masuk ke bangunan tengah dan menemui Ibu Dayu, istri Pak Mantra. Ibu Dayu menerima kami dengan ramah walau tampak hati-hati. Beliu bertanya, siapa kami, dari mana, mau bertemu siapa dan untuk apa. Setelah mengetahui identitas kami, beliau meminta kami menunggu sebentar, karena beliau menyampaikan kedatangan kami kepada Tu Aji (panggilan Pro Dr. Ida Bagus Mantra). Sesaat kemudian Ibu Dayu berbalik dan kembali bertanya, siapa yang memberitahu atau menyuruh kami menemui Pak Mantra. Dan seterusnya sampai kemudian Ibu Dayu menyampaikan, bahwa Pak Mantra berkenan menerima kami, namun jangan lama.
Benar saja. Saat itu kami diterima langsung oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Sosok yang kami kagumi karena kecintaan dan sayangnya kepada Bali. Beliau saat itu sedang tidak sehat, berbaring di ranjang khusus seperti di rumah sakit.
Kami pun memperkenalkan diri, satu persatu. Menyampaikan maksud dan tujuan, latar belakang dan harapan sangat besar menemui beliau. Saat saya menyampaikan kami berkunjung atas nama panitia Kongres Nasional I MHDI, beliau tampak berpikir berat, serius. Beliau belum pernah mendengar nama itu.
“Apa itu MHDI?” katanya. Kemudian mau apa ada panitia kongres nasional I MHDI?
Saat saya jawab tujuan pembentukan panitia kongres ini adalah untuk membentuk Ormas Kepemudaan Mahasiswa Hindu Indonesia, beliau menarik nafas dalam.
“Kan sudah ada organisasi pemuda Hindu seperti Peradah (yang ternyata Prof IB Mantra iktu membidani – pen),” tutur beliau.
“Untuk apa lagi membuat organisasi?” kata beliau bertanya.
Menurut beliau, mengapa mahasiswa Hindu tidak bergabung saja dengan Peradah (Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia). Bukankah mahasiswa juga bagian dari pemuda? Toh keberadaan organisasi pemuda Hindu saat itu juga tidak terlalu kuat dan efektif.
Kami pun menjelaskan latar belakang pemikiran membentuk wadah nasional bagi MHDI, antara lain untuk menyiapkan mahasiswa Hindu menjadi kader bangsa, kader umat dan kader penerus lembaga umat Hindu Indonesia, PHDI. Selain itu, dalam kancah nasional Indonesia, hanya mahasiswa Hindu yang belum memiliki organisasi. Mahasiswa umat lain sudah punya, seperti Islam dengan HMI, PMII dan lainnya, Kristen dan Katolik dengan GAMKI dan PKMRInya, mahasiswa Budha juga sudah membangun organisasi kemahasiswaan pemuda (OKP) dengan nama Gemabudhi (Gerakan Mahasiswa Budhisme). Mereka semua telah tergabung dalam OKP Cipayung Plus dan menjadi penggerak reformasi. Di akhir cerita, tidak lupa kami memohon perkenan dan kesediaan beliau untuk duduk menjadi penasehat panitia bersama sejumlah figure lain seperti Prof. dr. Ida Bagus Oka, Drs. Ida Bagus Oka Punia Atmadja, Anand Krishna, dan puluhan nama lainnya.
Pak Mantra mulai manggut-manggut. Beliau tampak mulai bersemangat. Menggeser posisi diri dari berbaring menjadi sedikit memiringkan badan. Beliau berusaha untuk duduk.
Di antara cerita yang kami sampaikan, tampak bahwa sepertinya beliau memiliki cerita terpendam yang panjang mengenai kelembagaan umat Hindu, khususnya kelembagaan yang mampu mencetak kader muda Hindu menjadi kader bangsa, memasuki dunia professional kerja, birokrasi, hingga kepemimpinan dan politik nasional untuk pada akhirnya bersedia dan siap mengabdi demi umat di lembaga PHDI.
Pak Mantra kemudian mulai bercerita tentang Praja Niti. Kiprah Praja Niti (yang ternyata juga ikut beliau bidani pembentukan dan kelahirannya), dan menyebut sejumlah nama. Dibalik cerita beliau, ada kerinduan yang dalam yang beliau simpan. Beliau ingin mendengar dan melihat kiprah generasi muda Hindu yang hebat di forum nasional. Termasuk bidang politik dan kepartaian (partai politik). Pak Mantra sepertinya sangat merindukan sosok generasi muda Hindu yang menyuarakan keberadaan dan aspirasi umat Hindu di level kebijakan nasional. Sehingga kebijakan nasional memberi ruang dan perhatian kepada Hindu secara lebih nyata. Bukan hanya menjadi anggota parpol dan anggota legislatif.
Setelah itu beliau bercerita mengenai harapan luas tentang lembaga majelis Hindu, PHDI. Tentang figure-figur yang mengisi PHDI, tentang kapasitas intelektual dan spiritualnya, dan tentang kiprah PHDI dalam arti luas. Bagaimana caranya PHDI bisa seperti lembaga majelis keumatan agama lain.
Beliau juga bercerita tentang asal usul munculnya pakaian hitam yang disebut sebagai pakaian berkabung saat orang atau keluarga ada yang meninggal, di Bali. Yang ternyata, bukan didasarkan atas ajaran dan nilai susatra Hindu, akan tetapi mengadopsi budaya Eropa dan merupakan kebijakan Pemprov Bali setelah Gubernur Bali Prof. dr. Ida Bagus Oka diundang ke Eropa. Dalam susastra Hindu, tidak dikenal warna pakaian tertentu sebagai warna berkabung. Merujuk kisah Mahabharata, jika dikaitkan dengan saat datang kematian, pakaian yang dikenakan justeru berwarna putih sebagai warna yang memiliki makna keikhlasan dan kembalinya jiwatman ke alam Brahman. Bukan hitam.
Beliau kemudian menegaskan, jika beliau nanti kembali ke alam Brahman, beliau meminta kepada orang-orang terdekatnya untuk tidak mengenakan pakaian warna hitam, tetapi sebaliknya mengenakan warna putih. Dan, itu beliau tulis sebagai wasiat. Dan benar, ketika beliau meninggal pada bulan Juli 1995, seluruh keluarga mengenakan pakaian putih, kompak. Terutama pada saat upacara pengabenan/pelebonan. Saya tidak melayat ke rumah duka karena setiap kali hendak ke sana, tidak mampu menahan haru dan tangis. Hanya doa sebagai seorang mahasiswa yang kami panjatkan untuk beliau.
Menjelang akhir pertemuan, Pak Mantra menjawab permohonan kami untuk menjadi penasehat panitia kongres nasional I MHDI, beliau mengajukan sebuah pertanyaan mengejutkan. Pertanyaan sederhana, namun sangat dalam kandungan maknanya.
“Setelah mendengar cerita ini, ada pertanyaan yang ingin Tuaji sampaikan. Di tengah kondisi umat Hindu seperti ini, kemudian generasi muda, seperti mahasiswa Hindu mengatakan ingin membentuk wadah untuk menyiapkan kader-kader bangsa dan kader penerus PHDI, berarti ada kerinduan dari generasi muda terhadap PHDI yang kuat. Bapak mau bertanya, seperti apa kerinduan generasi muda Hindu itu?”kata Pak Mantra.
“Apakah seperti anak merindukan ayah atau ibunya, atau seperti seorang murid yang merindukan gurunya, atau seperti atlet yang merindukan pelatihnya?” kata Pak Mantra.
Beliau meneruskan pertanyannya secara simbolik dengan meneliksik satu persatu dari kami yang berkunjung. Tak ada di antara beberapa rekan yang hadir berani menjawab dengan jelas, apalagi tegas, menjadikan suasana tidak menentu.
“Bapak keliling mencari jawaban atas pertanyaan ini, sampai ke India, sampai bertanya saat bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa di India,” lanjut Pak Mantra.
Jawaban yang beliau terima adalah seperti yang sudah beliau katakana sebelumnya, yakni seperti anak merindukan orangtua, seperti murid merindukan guru yang memberi tuntunan pelajaran, atau seperti atlet merindukan pelatihanya yang ingin berlatih keterampilan. Namun, jawaban itu tidak memberi kepuasan batin. Relung esoterik (batin) Pak Mantra merasakan bahwa jawaban itu belum mampu memenuhi hakekat kerinduan ruang batih spiritual yang sangat dalam.
“Bapak tidak puas dengan jawaban itu,” tegasnya sembari kembali menanyakan apakah ada diantara kami yang memiliki jawaban lain.
Ketika itu, saya sangat yakin dan mantap bisa menjawab. Namun belum siap menjawab di awal karena masih ada sejumlah rekan ikut hadir. Sejak awal Pak Mantra menyampaikan pertanyaan itu, yang terbayang dalam penglihatan batih saya adalah sebuah buku dengan cover tebal keras dan kuat berwarna putih, bertuliskan judul hitam yang didalamnya berisi sabda gita: Bhagawadgita.
Buku yang paling sering saya baca dalam mengisi kelemahan dan kekurangan diri saya yang diberi beban sangat berat sebagai Ketua Umum Panitia Kongres Nasional I MHDI dan harus sukses melahirkan wadah nasional KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia). Keadaan saya ketika itu sangat kekurangan. Sebagai mahasiswa, saya mahasiswa dari kampong, dari keluarga petani yang sangat sederhana, yang sudah selesai melakukan penelitian skripsi, namun rela menunda penyusunan skripsi karena tugas sejarah pendirian KMHDI ini.
Dengan yakin dan mantap akhirnya saya menjawab, “Kerinduan itu bukan seperti anak merindukan orangtua, juga bukan seperti murid merindukan guru Tu Aji, tetapi seperti Arjuna merindukan Krishna,” begitu saya menjawab dengan suara lemah.
“Apa?” begitu Pak Mantra seperti tersentak dan mendapat energi luar biasa. Beliau bergerak dari pembaringannya dan meminta saya untuk mengulangi jawaban .
“Katakan ning, katakan dengan lebih jelas, seperti apa? Seperti Arjuna apa?,” katanya.
“Seperti Arjuna mencari Krishna, Tuaji,” jawab saya.
“Ulangi ning, seperti apa,” katanya bergetar. Dan saya mengulangi dengan suara lebih keras, “Seperti Arjuna mencari Krishna.”
Pak Mantra sangat excited dengan jawaban itu. Beliau seperti mendapat kekuatan yang luar biasa, yang membebaskan dirinya dari beban batin yang berat dan lama.
“Seperti Arjuna mencari Krishna,” katanya mengulangi menatap saya dengan dalam.
“Seger bapak jani, seger. …. Bapak ini bapak. Jangan panggil Tu Aji, bapak ini bapak,” begitu beliau saat itu.
“Puas bapak, puas,” katanya berulang-ulang menyalami kami.
“Dija cening maan jawaban keto?” katanya meneliksik. Dan saya jawab, saya mendapatkannya di buku Bhagawadgita yang beliau terjemahkan.
Pak Mantra tak menyangka pada keajaiban itu. Beliau sangat senang dan bahagia. Beliau pun langsung duduk. Hingga kami bercerita jauh lebih lama dari waktu yang semula diberikan Ibu Dayu, 20 menit. Hampir 2 jam kami bercerita saat itu.
Dan pada saat itu juga beliau menyatakan bersedia menjadi penasehat panitia kongres, dan berjanji hadir langsung dalam arena Kongres Nasional I MHDI di Kampus Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar (kampus yang beliau inisiasi) pada bulan September 1993.
Dan, beliau menepati janjinya. Prof Dr. Ida Bagus Mantra hadir langsung menyaksikan suasana kongres yang saya selenggarakan bersama mahasiswa Hindu seluruh Indonesia.
Kisah ini penting saya tulis dan sampaikan di ruang publik, agar generasi muda Hindu Indonesia mendapat informasi langsung mengenai perjalanan saya dalam memimpin Panitia Kongres Nasional I MHDI menyiapkan pelaksanaan kongres pada 1 – 3 September 1993 dan melahirkan KMHDI. Saya pribadi sangat terkesan pada momentum itu dan tidak bisa melupakannya.
Hikmah terdalam dari pertemuan kami itu adalah saya dan Pak Mantra dihantarkan ke dalam titik-temu batiniah mengenai cita-cita persiapan pembentukan KMHDI. Cita-cita pembelajaran bahwa dalam konflik aneka situasi, Arjuna lebih memilih Krishna sendiri sebagai “senjata” dalam perang Mahabharata, dan bukan memilih senjata dan prajurit dalam jumlah bear, kuat dan canggih. Di saat yang sama, Korawa dibawah pimpinan Duryodhana memilih prajurit dan senjata milik Prabhu Krishna.
Terimakasih telah mengikuti kisah ini, semoga menginspirasi.
Penulis: I Dewa Putu Gandita Rai Anom, S.TP. (Ketua umum panitia Kongres Nasional I Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia 1992/1994)