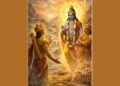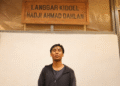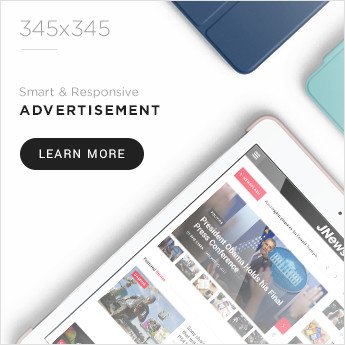“Tradisi yang diwariskan tanpa makna hanya akan jadi beban yang dijunjung, bukan jalan yang menyala.”
Satu Wajah yang Terlalu Lama Dikenakan
Di tengah padatnya lalu lintas ide dan identitas di tanah rantau, saya kerap merasa Hindu itu seperti ruang sempit yang hanya bisa ditempati oleh mereka yang membawa adat Bali. Di banyak diskusi, perayaan, bahkan dalam pelajaran agama di sekolah, Hindu selalu dikaitkan dengan gamelan, banten, odalan, dan segala ornamen budaya Bali. Seolah-olah Hindu lahir di Pulau Dewata, tumbuh besar di kaki Gunung Agung, dan tidak punya tempat di luar batas itu.
Saya sendiri lahir dan besar di Jawa Barat, meskipun berasal dari keluarga Bali. Di rumah, saya hidup dalam nafas tradisi Bali—dari bahasa, busana, hingga kebiasaan upacara. Tapi di luar rumah, saya tumbuh bersama teman-teman dari berbagai latar belakang. Saya belajar bahwa jadi Hindu tak selalu harus seperti yang diajarkan di rumah. Ada banyak wajah Hindu di luar sana—dan itu membuat saya bertanya: apakah kita sudah cukup adil dalam memahami keberagaman ini?
Di Antara Simbol dan Makna
Semakin saya belajar, semakin saya merasa: ada yang keliru dalam cara kita memahami agama ini. Kita seringkali lebih setia pada tradisi, daripada pada nilai yang melandasinya. Kita lebih khusyuk membela simbol, daripada menggali makna yang ada di dalamnya.
Masalahnya bukan pada Bali—Bali adalah taman kearifan yang luar biasa. Tapi ketika ekspresi Hindu dari Bali diklaim sebagai satu-satunya wajah Hindu yang sah, maka di situlah akar masalahnya tumbuh. Hindu jadi seperti milik eksklusif sebuah etnis, padahal sejarah dan teks-teks suci Hindu sendiri berbicara tentang pluralitas tafsir, kebebasan berpikir, dan jalan yang beragam menuju kebenaran.
Banyak orang mengenal Hindu di Indonesia dari apa yang terlihat di Bali: canang yang indah, pura yang megah, gamelan yang sakral, dan upacara-upacara yang menggugah mata. Wajar, mengingat Bali telah menjadi etalase Hindu Indonesia di mata dunia. Namun di balik keindahan itu, muncul persoalan yang kerap tak disadari: dominasi satu ekspresi budaya terhadap pemaknaan keagamaan secara keseluruhan.
Tafsir yang Mengakar pada Satu Budaya
Kita tidak sedang mempermasalahkan Bali. Kita justru mengakui betapa kuat dan gigihnya masyarakat Bali dalam mempertahankan warisan spiritualnya. Namun yang menjadi soal adalah ketika narasi Hindu di Indonesia secara perlahan—bahkan sistematis—dimonopoli oleh tafsir kultural yang Bali-sentris. Hindu kemudian dianggap sebagai kelanjutan adat Bali, bukan sebagai jalan spiritual yang melampaui batas etnis.
Sebagai umat Hindu di rantau, terutama di wilayah seperti Jawa Barat, kita hidup berdampingan dengan realitas plural: dari Hindu Kaharingan di Kalimantan, Hindu Jawa yang menyatu dalam keheningan tradisi, hingga umat Hindu diaspora yang membangun pura di tengah kota. Masing-masing membawa cara hidup, cara sembah, dan cara memahami dharma yang berbeda. Perbedaan ini bukan ancaman. Justru di sanalah letak kekayaan yang seharusnya dirawat.
Antara Lahir dan Warisan
Saya besar dengan satu anggapan yang terus menerus direproduksi di banyak ruang percakapan umat: bahwa menjadi Hindu berarti menjadi Bali, dan menjadi Bali berarti otomatis Hindu. Kalimat ini sering terdengar sederhana, bahkan terdengar logis bagi sebagian orang. Tapi semakin saya menua, semakin terasa sesaknya.
Di sekolah dulu, saya pernah ditanya: “Kamu orang Bali, berarti Hindu ya?”
Sementara di lain tempat, di antara sesama umat Hindu, saya justru pernah dipertanyakan: “Itu lah lahir di (pulau) Jawa! Jadi nggak mengerti soal upacara Hindu.”
Saya berada di persimpangan yang membingungkan: dianggap terlalu Hindu di luar, tapi kurang Bali di dalam.
Refleksi Diri dari Tanah Rantau
Kadang, kita yang hidup di rantau terlalu mudah merasa cukup hanya dengan menjaga bentuk. Kita bangga mengenakan kamen saat ke pura, menata canang saat Galungan, atau membuat banten dari janur yang dipotong sedemikian rupa. Tapi benarkah kita memahami makna di baliknya? Atau jangan-jangan, justru kita yang menjadikan budaya itu sekadar ornamen?
Ironisnya, sebagian orang Bali dari tanah asal malah mempertanyakan: apakah yang kita jaga di rantau benar-benar dharma, atau hanya estetika? Apakah yang kita pelajari di banjar benar-benar adat, atau hanya simbol yang dipoles agar tampak ‘berbudaya‘? Pertanyaan ini bukan untuk meremehkan, tapi mengingatkan: bahwa menjaga warisan tidak cukup dengan bentuk. Harus ada rasa. Harus ada pemahaman.
Karena kalau kita sendiri tak berani menyelami maknanya, bagaimana bisa kita menuntut pengakuan dari luar?
Keragaman Hindu yang Terlupakan
Di balik label yang kita warisi secara kultural itu, saya kemudian menyadari ada banyak umat Hindu lain di Nusantara yang mengalami hal yang sama, atau bahkan lebih rumit. Mereka yang tidak lahir di Bali, tidak menggunakan bahasa Bali, tidak mengenal canang sari, tapi tetap memuja Sang Hyang Widhi dengan caranya sendiri. Mereka yang jauh dari Bali, tapi tetap menjaga dharma.
Mari sebut satu per satu:
- Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah yang bersumber dari kepercayaan Dayak dan kini menjadi agama resmi dengan nama “Hindu.”
- Hindu Tengger di lereng Bromo yang tetap teguh dengan sesajen, upacara Kasada, dan ajaran leluhur.
- Hindu Tolotang di Sulawesi Selatan yang hidup berdampingan dengan Islam dan Kristen tanpa pernah kehilangan spiritualitasnya.
- Hindu Sidderap dan Hindu Buru yang berakar dari tradisi lokal, juga Hindu Pemena yang menjadi nafas spiritual suku Karo di Sumatera Utara.
- Hindu Tamil di Medan yang sejak abad ke-19 telah menjaga warisan spiritual dari India Selatan, dengan ritual, bahasa, dan dewa-dewa yang mungkin asing bagi umat Hindu mayoritas, namun tetap satu dalam penghormatan pada dharma.
Semua mereka adalah Hindu. Tapi sayangnya, tak semua dari kita siap mengakui bahwa Hindu tidak harus berbau Bali.
Menuju Hindu yang Lebih Inklusif
Mungkin ini luka yang harus kita obati pelan-pelan. Karena terlalu lama narasi ke-Hindu-an di Indonesia terjebak dalam semacam “monopoli kultural“. Bali seakan menjadi satu-satunya etalase Hindu. Dan ketika umat dari luar Bali mencoba menyuarakan bentuk ke-Hindu-annya sendiri, mereka justru sering dianggap aneh, tidak sah, atau lebih parah: menyimpang.
Saya tidak sedang mengajak untuk menolak Bali. Justru sebaliknya—saya bersyukur lahir dari keluarga Bali yang menjaga ajaran dengan penuh ketekunan. Tapi saya juga merasa ada hal yang perlu diluaskan: bahwa Hindu adalah jalan spiritual yang sudah lebih dulu menyatu dengan banyak peradaban di Nusantara, jauh sebelum Indonesia bahkan berdiri. Hindu adalah jembatan antara manusia dengan alam semesta, bukan monopoli adat dan bahasa.
Kita perlu menyadari bahwa agama ini hidup karena keberagaman tafsir dan ekspresi. Ia tumbuh di tanah-tanah berbeda, dengan ritus dan mitos yang tidak seragam. Hindu di pedalaman Kalimantan tidak perlu memakai udeng untuk disebut sah. Hindu di lereng Gunung Bromo tidak harus paham lontar-lontar warisan Bali untuk disebut beriman. Dan saya, yang lahir sebagai Hindu di Jawa Barat, tak harus menjadi “lebih Bali” untuk berhak merasa menjadi bagian dari umat ini.
Barangkali inilah pekerjaan rumah kita bersama: membuka mata dan hati, lalu mengakui dengan jujur bahwa Hindu bukan milik satu pulau saja. Ia adalah denyut yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari altar bambu di desa, hingga temaram dupa di kota-kota.
Dan ketika kita mulai merayakan keberagaman itu, mungkin barulah kita layak menyebut diri sebagai umat Hindu Nusantara.
Penulis : Lingga Dharmananda Siana (Fungsionaris PP KMHDI)